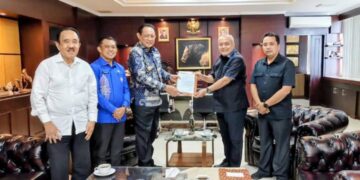PROSESNEWS.ID – Dunia menyaksikan luka yang terus menganga di Palestina. Penjajahan yang terjadi di tanah kelahiran para Nabi itu bukan hanya merampas wilayah, tetapi juga menelan nyawa demi nyawa, termasuk anak-anak dan perempuan yang tak berdosa. Gambar dan video kekejaman itu hadir setiap hari di hadapan kita, membekas di hati mereka yang masih memiliki nurani.
Namun, di tengah situasi tragis ini, betapa menyakitkannya melihat seorang pemimpin negara secara terbuka menyatakan dukungan terhadap entitas penjajah dengan menyebutnya sebagai negara yang berdaulat dan harus dijamin keamanannya. Ini jelas merupakan pernyataan yang keliru dan menyesatkan. Bagaimana mungkin sebuah entitas hina yang telah merampas kedaulatan dan kemerdekaan Palestina—dengan tindakan kekerasan dan penjajahan yang begitu kejam—justru diberi legitimasi dan pengakuan sebagai negara sah serta mendapatkan jaminan keamanan?
Dukungan yang dibalut narasi diplomasi ini sejatinya adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan sejarah solidaritas. Lebih tragis lagi, negara yang dipimpin oleh sosok tersebut dahulu pernah pertama kali diakui kemerdekaannya oleh Palestina—sebuah fakta sejarah yang seolah dilupakan begitu saja.
Yang lebih ironis, dukungan itu datang dari seorang pemimpin yang negaranya sendiri tengah berada di ambang krisis multidimensi. Penegakan hukum di negaranya amburadul—aparat hukum yang mudah disuap, praktik korupsi yang merajalela, dan sistem hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Ketimpangan sosial terus melebar, kemiskinan meningkat, pengangguran membayangi masa depan generasi muda, dan kualitas pendidikan pun kian timpang.
Negeri itu juga didera berbagai masalah lingkungan akibat pembiaran penebangan liar dan pengelolaan sampah yang buruk. Berbagai kebijakan yang diterapkan justru merugikan rakyat: pajak mencekik, utang negara membengkak, dan keputusan-keputusan publik yang jauh dari akal sehat serta keadilan sosial.
Dalam kondisi seperti ini, publik patut bertanya: Apa urgensinya melakukan manuver politik luar negeri dengan mendukung negara penjajah, sementara negeri sendiri tengah tenggelam dalam tumpukan persoalan? Bukankah lebih bijak jika energi dan sumber daya diarahkan untuk memperbaiki kondisi internal negeri? Itupun sepaarah-parahnya krisi-empati.
Maksud saya, bagi pemerintah negara yang krisi-empati terhadap kondisi rakyat Palestina, jika memang tidak mampu mengambil tindakan langsung di medan konflik, paling tidak tindakan yang dilakukan adalah menyatakan dukungan atau keberpihakan terhadap Palestina itu sendiri. Bukan justru memberi obat penenang kepada pihak yang jelas-jelas mengancurkan ketenangan bangsa lain.
Saya pikir, tindakan pemimpin tersebut sangat mungkin membuat sebagian besar rakyatnya merasa malu—malu karena dipimpin oleh seseorang yang tidak mencerminkan sikap adil, beradab, dan berintegritas. Rakyat yang masih memiliki nurani tentu tidak rela jika nama bangsa mereka dicatat dalam sejarah sebagai pendukung penindasan dan penjajahan.
Seorang pemimpin dinilai bukan dari seberapa nyaring suaranya di panggung internasional, tetapi dari seberapa kuat komitmennya memperjuangkan keadilan, baik di dalam maupun luar negerinya. Dan bagi saya, ketika suara yang ia keluarkan justru melukai sejarah persahabatan dan solidaritas dengan bangsa tertindas seperti Palestina, maka publik berhak menyebutnya sebagai pengkhianatan moral.
Palestina tidak butuh dukungan dari negara besar, tetapi dari negara yang masih memiliki integritas. Dan dunia tidak butuh pemimpin yang berpura-pura peduli kemanusiaan sambil menutup mata terhadap genosida yang sedang berlangsung.